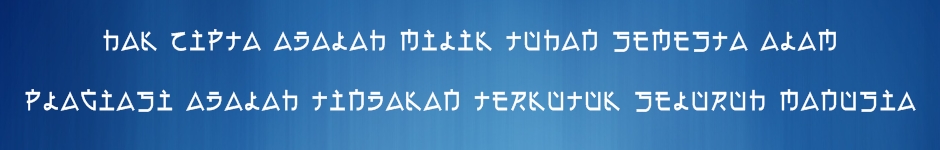Oleh
Mokhamad Sukron
Pendahuluan
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang hingga saat ini menjadi kunci yang paling mendasar dari kemajuan peradaban umat manusia tentu tidak dapat diraih begitu saja tanpa ada sebuah dinamika atau diskursus ilmiah. Proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah epistemologi. Epistemologi sendiri secara bahasa adalah bentukan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang juga berarti pengetahuan atau informasi.[1]Dengan kata lain, epistemologi adalah pengetahuan tentang pengetahuan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh The Liang Gie dalam bukunya Pengantar Filsafat Ilmu, bahwa:
“Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas berbagai segi pengetahuan seperti kemungkinan, asal mula sifat alami, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas dan realibilitas sampai soal kebenaran.”[2]
Oleh karena itu, epistemologi mempunyai peran dan kedudukan penting dalam proses mencari dan menentukan pengetahuan yang benar, dimana kepiawaian epistemologi seseorang akan mempengaruhi pada warna atau jenis ilmu pengetahuan yang dihasilkan.
Dalam Islam sendiri, filsafat ilmu sampai sekarang belum ada buku yang membahasnya secara spesifik. Oleh karena itu untuk menempatkan kedudukan filsafat pengetahuan dalam Islam, aspek-aspek yang dimilikinya patut dipertimbangkan. Seperti tingkatan-tingkatan perjalanan epistemilogi dalam Islam diantaranya: (a) perenungan (contemplation) tentang Sunatullah sebagaimana dianjurkan dalam al-Qur’an, (b) penginderaan (sensation), (c) penyerapan atau tanggapan daya memahami (perception), (d) penyajian (representation), (e) konsep, (f) timbangan (judgement) dan (g) penalaran (reasoning).[3] Epistemologi dalam Islam tidak berpusat pada manusia saja yang menganggap manusia sendiri sebagai makhluk mandiri dan menentukan segala-galanya, melainkan berpusat kepada Allah swt, sehingga berhasil atau tidak berhasilnya manusia dalam menentukan kebenaran suatu pengetahuan tergantung pada usaha manusia sendiri dan itupun belum bisa dikatakan sebagai suatu kebenaran. Karena seperti apa yang dikatakan Imam Syafi’i bahwa kebenaran yang ada pada pendapatku mengandung unsur kesalahan begitu pula sebaliknya kesalahan yang ada pada selain pendapatku ada kebenaran di dalamnya yang pada suatu saat nanti akan berlaku sesuai dengan zaman. Jadi, kebenaran suatu pengetahuan dalam Islam adalah berpusat pada diri Allah sendiri, sedangkan manusia adalah berfungsi sebagai subyek pencari kebenaran.[4]
Menurut al-Jabiri, epistemologi mengacu pada serangkaian prinsip-prinsip dasar yang dihasilkan oleh suatu budaya tertentu sebagai landasan (kerangka dasar) aktivitas pemerolehan pengetahuan (sistem epistemik), dan produksi pengetahuan[5]. Ini berarti, epistemologi merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menata pengalaman dan mengarahkan tanggapan terhadap dunia luar sebagai realitas yang disadari. Dan ditemukan olehnya bahwa memperoleh ilmu pengetahuan bisa diraih dengan tiga model epistemologi yaitu: (1)epistemologi Bayani, (2) epistemologi Irfani dan (3)epistemologi Burhani. Karena menurut al-Jabiri, Tradisi (turaș) Islam sama sekali berbeda dengan tradisi lain, bukan pula sekedar karya – karya atau pandangan ulama terdahulu sebagaimana yang dipahami kaum tradisional. Tradisi Islam adalah segala yang secara asasi berkaitan dengan aspek pemikiran dalam peradaban Islam, mulai dari ajaran doktrinal, syariat, bahasa, sastra, seni, teologi, filsafat dan tasawuf. Artinya tradisi dalam problem historis yang bergolak di antara satu sama lain, saling mengisi, saling kritik, bahkan saling jegal. Karena itu, ia tidak bisa dikaji dengan pendekatan materialism historis[6], seperti yang lazim digunakan kaum orientalis, tetapi harus dikaji dengan metode – metode khusus yakni strukturalis, analisis sejarah, kritik ideologis.
Biografi dan Karir Intelektual Muhammad ‘Abid al-Jabiri
Muhammad ‘Abid al-Jabiri lahir di Figuig, sebelah selatan Maroko pada tahun 1936 M. dan pendidikannya dimulai dari tingkat ibtidaiyah di madrasah Burrah Wataniyyah, yang merupakan sekolah agama swasta yang didirikan oleh oposisi kemerdekaan. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah dari tahun 1951-1953 di Casablanca dan memperoleh Diploma Arabic high School setelah Maroko merdeka. Sejak awal al-Jabiri telah tekun mempelajari filsafat. Pendidikan filsafatnya di mulai tahun 1958 di univeristas Damaskus Syiria, namun al-Jabiri tidak bertahan lama di universitas ini. Setahun kemudian ia berpindah ke universitas Rabat yang baru didirikan. Kemudian ia menyelesaikan program Masternya pada tahun 1967 dengan tesis Falsafah al-Tarikh ‘Inda Ibn Khaldun, di bawah bimbingan N. Aziz Lahbabi ( w.1992), dan gurunya juga seorang pemikir Arab Maghribi yang banyak terpengaruh oleh Bergson dan Sarter.[7]
Al-Jabiri semasa mudanya merupakan seorang aktivis politik berideologi sosialis. Dia bergabung dengan partai Union Nationale des Forces Populaires (UNFP), yang kemudian berubah menjadi Union Sosialiste des Forces Populaires (UNSFP). Pada tahun 1975 dia menjadi anggota biro politik USFP.[8]Di samping aktif dalam politik, al-Jabiri juga banyak bergerak di bidang pendidikan. Dari tahun 1964 ia telah mengajar filsafat di Sekolah Menengah, dan secara aktif terlibat dalam program pendidikan nasional. Pada tahun 1966 dia bersama dengan Mustafa al-Qamari dan Ahmed Sattati menerbitkan dua buku teks, pertama tentang pemikiran Islam dan kedua mengenai filsafat, untuk mahasiswa S1.[9]
Karya-karyanya Al-Jabiri telah menghasilkan berpuluh karya tulis, baik yang berupa artikel koran, majalah atau berbentuk buku. Topik yang selalu diangkatnya juga bervariasi dari isu sosial dan politik hingga filsafat dan teologi. Karir intelektualnya seperti dimulai dengan penerbitan buku Naḫnu wa al-Turaș-nya, disusul dua tahun kemudian dengan al-Khitab al-’Arabi al-Mua’shir Dirasah Naqdiyyah Taḫliliyyah, kedua buku tersebut seperti sengaja dipersiapkan sedemikian rupa sebagai pengantar kepada grand proyek intelektualnya Naqd al-’Aql al-’Arabi (kritik akal Arab).[10]
Tulisan ini bertujuan sebagai upaya untuk membongkar formasi awal pemikiran Arab-Islam dan mempelajari langkah apa saja yang dapat diambil dari pemikiran Islam klasik tersebut. Untuk karya ini telah menerbitkan Takwim al-’Aql al-’Arabi, Bunyah al-’Aql al-’Arabi, al-A’ql al-Siyasi al-’Arabi, al-’Aq al-Akhalqi al Arabiyyah, Dirasah Taḫliliyah Naqdiyyah li Nudzum al-Qiyam fi al-Ṣaqafah al-Arabiyyah. Karya terpentingnya yang termasuk al-Turâș wa al-Ḫadâșah, Isykâliyyah al-Fikr al-’Arabi al-Mu’âshir, Tahafual al-thafut intisaran li ruh al-Ilmiyyah wa ta’sisan li akhlaqiyat al-Hiwar, Qadaya al-Fikr al ‘Mu’âshir Al’awlamah, Sira’ al-Ḫadarât, al-Wahdah ila al-Ahklaq, al-Tasâmuh, al-Dimaqratiyyah. Tahun 1996, al-Mashru al-Nahdawi al-’Arabi Muraja’ah naqdiyayh, al-Din wa al Dawlah wa Thabiq al-Syari’ah, Mas’alah al-Hawwiyah, al-Muthaqqafun fi al-Hadarah al-’Atabiyyah Mihnab ibn Hambal wa Nukkhah Ibn Rusyd, al-Tahmiyyah al-Basyaraiyyah di al-Watan al-‘Arabi.[11]
Pengertian Bayani, Burhani dan Irfani
Pengetahuan manusia pertama kali diperoleh adalah melalui panca indera yang mengamati obyek-obyek fisik. Kemudian diikuti oleh akal yang mampu mengenal objek fisik dan nonfisik dengan menyimpulkan dari yang telah diketahui menuju yang tidak diketahui. Selanjutnya beralih kepada peran hati, dimana ia menangkap nonfisik atau metafisika melalui kontak langsung dengan objek yang hadir dalam jiwa. Ketiga organ tubuh itulah yang menjadi alat atau media dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Sebuah pengetahuan akan diperoleh melalui pendengaran atau bisa disebut Bayani, yakni mengandalkan pendengaran akan teks-teks yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, atau melalui penglihatan dengan menganalisa apa yang dilihat dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan para pengikutnya, sedangkan hati dapat mengantarkan seseorang untuk menimbang mana yang terbaik untuk diterapkan.
Epistemologi Bayani
Secara etimologi, al-Jabiri memberikan empat pengertian terhadap Bayani, yakni: al-fashl wa al-infishâl (memisahkan dan terpisah) dan al-dhuhūr wa al-idhhâr (jelas dan penjelasan). Konsep pertama berkaitan dengan metodologi sementara konsep kedua berkaitan dengan ru’y (visi) dari metode Bayani. Dengan kata lain, Bayani yang berarti al-fashl wa infishâl adalah metode sementara Bayani yang berarti al-dhuhūr wa al-idhhâr berarti visi atau ru’y. Sedangkan secara terminologi, Bayani memiliki dua arti: pertama, sebagai aturan-aturan penafsiran wacana (qawânin tafsir al-kitab) dan kedua, sebagai syarat-syarat memproduksi wacana (syurūth intâj al-khitâb). Epistemologi Bayani meliputi disiplin-disiplin ilmu yang menjadikan ilmu bahasa Arab sebagai tema utamanya, seperti nahwu (gramatika bahasa Arab), fiqh, ushūl al-fiqh, kalam dan balâghah (ilmu seni bahasa).[12] Dengan begitu al-Jabiri mengartikan Bayani adalah sebagai nama universal (isim jami’) sebagaimana yang ia jelaskan dengan mengutip pendapat al-Jahiz dalam kitabnya al-bayân wa al-tabyin dan pendapat imam Syafi’i, yang menyatakan bahwa Bayani merupakan nama universal yang mengandung berbagai macam makna yang mempunyai prinsip-prinsip yang sama namun cabangnya berbeda-beda.[13] Menurut al-Jabiri, corak epistemologi Bayani didukung oleh pola pikir fiqih dan kalam. Jika melihat dalam tradisi keilmuan Islam, corak pemikiran Islam model Bayani sangatlah mendominasi dan bersifat hegemonik sehingga menjadi sulit berdialog dengan tradisi epistemologi Irfani maupun Burhani.
Corak pemikiran Irfani (tasawuf) kurang begitu disukai oleh tradisi berpikir keilmuan Bayani (fiqih dan kalam)yang murni, lantaran bercampur-aduknya dan dikabur-buramkannya tradisi berpikir Irfani oleh kelompok-kelompok tarekat. Terlebih pola pikir Irfani dan struktur fundamental epistemologi Irfani serta nilai manfaat yang terkandung di dalamnya cenderung sulit dipahami. Padahal ketiganya merupakan epistemologi yang masih satu rumpun dalam epistemologi ulūm al-din tetapi dalam prakteknya hampir tidak pernah akur. Maka tidak heran jika antar masing-masing penganut saling mengklaim kebenaran masing-masing dan berujung pada saling kafir-mengkafirkan atau murtad-memurtadkan. oleh karena itu, pola pikir tekstual Bayani ini secara politis sangat mendominasi yang kemudian membentuk pola pikir Islam yang hegemonik dan implikasinya pola pikir Bayani ini menjadi kaku. Otoritas-otoritas teks dan kaidah-kaidah metodologi yang dibakukan dalam ushūl al-fiqh klasik lebih diunggulkan dibandingkan dengan sumber keilmuan lain seperti alam, akal dan intuisi.[14]
Dalam tradisi nalar epistemologi Bayani, fungsi akal hanya digunakan sebatas untuk mengukuhkan dan membenarkan otoritas teks. Namun, di luar kalkulasinya apakah pelaksanaan dan implementasi ajaran teks dalam kehidupan masyarakat luas masih semurni dan seasli teks itu sendiri atau tidak? Karena diskusi semacam itu akan diintrodusir dan diambil-alih oleh pola pemikiran Burhani. Sejak awal memang pola pikir Bayani lebih mendahulukan qiyas dan bukannya mantiq lewat silogisme dan premis-premis logika. Epistemologi tekstual-lughâwiyyah lebih diutamakan daripada epistemologi kontekstual-baḫṣiyyah maupun spiritualitas-‘irfâniyyah-bâthiniyyah. Di samping itu, nalar epistemologi Bayani selalu mencurigai akal pikiran, karena dianggap akan menjauhi kebenaran tekstual. Samapi-sampai muncul kesimpulan bahwa wilayah kerja akal pikiran perlu dibatasi sedemikian rupa dan perannya dialihkan menjadi pengatur dan pengekang hawa nafsu, bukannya untuk mencari sebab-akibat lewat analisis keilmuan yang akurat.[15]
Oleh karena itu, secara langsung Bayani adalah memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Namun secara tidak langsung Bayani berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Sehingga dalam Bayani, akal dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode Bayani adalah aspek eksoterik (syariat).[16] Bisa disederhanakan dalam bahasa filsafat bahwa pendekatan Bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal ini teks sucilah yang memilki otoritas penuh menentukan arah kebenaran. Fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya yang dapat diketahui melalui pencermatan hubungan antara makna dan lafadz.[17]
Epistemologi Irfani
Kata Irfan adalah bentuk mashdar dari kata ‘arafa yang berarti ma’rifat (ilmu pengetahuan).[18] Kemudian irfan lebih dikenal sebagai terminologi mistik yang secara khusus berarti ma’rifat dalam pengertian pengetahuan tentang Tuhan. Kalau ilmu (pengetahuan eksoterik) yakni pengetahuan yang diperoleh indera dan intelek melalui istidlâl, nadzar dan burhan, maka irfan (pengetahuan esoterik) yaitu pengetahuan yang diperoleh qalb (hati) melalui kasyf, ilham, ’iyân (persepsi langsung), dan isyrâq.[19] Oleh Karena itu, Irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakekat oleh Tuhan kepada hambanya (kasyf) setelah adanya olah rohani (riyadhah) yang didasarkan atas dasar cinta (maḫabbah). Dan maḫabbah inilah yang mempercepat seorang hamba ma’rifat (mengetahui hakekat). Mengenai ma’rifat, yakni mengenal Allah dalam hati yang sebenarnya, itu merupakan tujuan para sufi. Al-Ghazali berpendapat bahwa ma’rifat akan dapat dicapai dengan hati yang bersih. Artinya hati yang bersihlah yang bisa menerima Nur Allah untuk mengenal sesuatu dalam hati yang sebenarnya. Syarat pertama yang harus dilakukan adalah mensucikan hati dari yang selain Allah Swt. Kunci itu adalah melibatkan hati secara total untuk berdzikir (ingat) kepada Allah dan akhir dari kesucian itu adalah fana’ secara total menuju Allah.[20]
Perpaduan teks dan akal ternyata memunculkan kekakuan dan ketegangan-ketegangan tertentu bahkan tidak jarang menimbulkan konflik dan kekerasan yang bersumber dari pola pikir ini. Untuk menghindari kekakuan dalam berpikir keagamaan yang menggunakan teks sebagai sumber utamanya, epistemologi pemikiran Islam sesungguhnya telah mempunyai dan menyediakan mekanisme kontrol keseimbangan dari dalam melalui epistemologi Irfani, yang lebih bersumber pada intuisi. Kemudian status keabsahan Irfani sendiri selalu dipertanyakan baik oleh tradisi Bayani maupun Burhani. Karena epistemologi Bayani menganggap keabsahan Irfani tidak mengindahkan pedoman-pedoman yang diberikan teks, sedangkan epistemologi Burhani mengangap keabsahannya tidak mengikuti aturan dan analisa logika. Memang sulit untuk mengembalikan citra positif epistemologi Irfani dalam pangkuan gugus epistemologi Irfani yang lebih komprehensif-integrated karena kecelakaan sejarah hal kedekatannya dengan perkumpulan tarekat. Padahal tarekat itu sendiri adalah institusi dari Gnosis (Tasawuf) dalam budaya Islam.[21]
Sebagaimana yang dipaparkan al-Jabiri dengan mengutip pendapat al-Qusyairi, tradisi tasawuf sendiri sejak mulanya telah membedakan derajat pengetahuan menjadi tiga sistem, dan kemudian mencari rujukannya pada nash al-Qur’an. teks tersebut adalah QS. al-Waqi’ah: 95 “haqul yaqin” adalah pengetahuan Irfani, QS. al-Takatsur: 5 “ilm al-yaqin” adalah Burhani dan QS. al-Takatsur: 7 “ayn al-yaqin” adalah untuk pengetahuan Bayani. Kemudian al-Jabiri menambahkan bahwa Irfani memilki dua sisi yang saling berhubungan. Satu sisi sebagai world view (pandangan dunia) pengikutnya, hyang bersifat pribadi dalam mengatur segenap prilaku dan cara pikir mereka yang intinya bermuara pada pelarian diri dari realitas. Sisi lain Irfani juga melahirkan referensi teoritis untuk menafsirkan alam, manusia dan realitas lainnya.
Dhahir-bathin dan wilayah-nubuwwah dalam epistemologi Irfani merupakan pasangan penting dalam rangka membentuk metode dan pola pandang terhadap realitas. Pasangan dhahir-bathin merujuk pada proses penalaran yang berangkat dari yang bathin ke arah yang dhahir atau lafadz menuju ma’na. Pertautan keduanya bukan dibangun diatas landasan asas universalitas dan keharusan, melainkan hanya bersifat parsial dan individual. Sementara itu, metode untuk menautkan pasangan bathin sebagai al-ashl dan dhahir sebagai al-far’ tersebut merupakan riyadlah mujahadah dengan qiyas sebagai kerangka teoritiknya. Namun perlu digaris bawahi bahwa qiyas ini sangatlah berbeda dengan qiyas Bayani apalagi qiyas Burhani.[22]
Epistemologi Burhani
Al-Burhân dalam bahasa Arab berarti argument yang clear dan distinct. Dalam pengertian logika, al-burhân adalah aktivitas pikir yang menetapkan kebenaran sesuatu melalui penalaran dengan mengkaitkan pada pengetahuan yang bukti-buktinya mendahului kebenaran. Sedangkan dalam pengertian umum, al-burhân berarti aktivitas pikir untuk menetapkan kebenaran sesuatu.[23] Al-Jabiri menggunakan Burhani sebagai sebutan terhadap sistem pengetahuan yang berbeda dengan metode pemikiran tertentu dan memiliki world view tersendiri, yang tidak bergantung pada hegemoni sistem pengetahuan lain. Burhani mengandalkan kekuatan indera, pengalaman, dan akal dalam mencapai kebenaran. Metode Burhani tersebut dapat diterapkan jika memenuhi beberapa tahap: pertama, tahap pembuatan pengertian yang mencakup jenis, nau’, dan fashl. Kedua, tahap pembuatan kalimat. Ketiga, tahap pembuatan silogisme. Silogisme adalah cara berargumen dengan dua premis dan satu kesimpulan.[24]
Karena itu, silogisme harus terdiri dari tiga hal, yaitu: (1) dua premis yang saling berhubungan, (2) premis pertama disebut premis mayor dan premis yang kedua disebut premis 14 minor, dan (3) premis penengah yang merupakan kesimpulan. Ketiga kecenderungan epistemologis Islam ini, secara teologis mendapatkan justifikasi dari al-Qur’an. Dalam al-Qur’an banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang pengetahuan yang bersumber pada rasionalitas. Perintah untuk menggunakan akal dengan berbagai macam bentuk kalimat dan ungkapan merupakan suatu indikasi yang jelas untuk hal ini. Akan tetapi, meskipun demikian, tidak sedikit pula paparan ayat-ayat yang mengungkapkan tentang pengetahuan yang bersumber pada intuisi (hati atau perasaan) terdalam.
Berangkat dari Hellenisme Yunani yang spekulatif-kontemplatif, para sarjana muslim pada masa kejayaannya leluasa menyerap, kemudian memodifikasi menjadi tradisi filsafat sains yang berangkat dari postulat-postulat al-Qur’an dengan mengetengahkan tradisi berfikir empirikal-eksperimental. Usaha tersebut dilakukan dengan mendayagunakan perangkat-perangkat intelektual sebagai jalan mencari jawaban tentang hakikat realitas, baik yang nyata (fisis) maupun yang gaib (metafisis). Dari revolusi filsafat di tangan kaum muslimin ini, lahirlah konsep ilmu atau sains yang tegak di atas 15 postulat-postulat Qur’ani.[25]
Kritik Al-Jabiri Terhadap Epistemologi Nalar Arab
Melihat perihal diatas, tentu saja epistemologi Bayani merupakan sebuah sistem yang menghegemoni tradisi Arab Islam. Teori yang dibawa Bayani adalah al-qiyâs al-bayâni sebagai imbangan al-qiyâs al-irfâni dan al-qiyâs al-burhâni. Qiyas-Bayani merupakan teori sekaligus struktur spirit dalam wilayah Bayani yang mencakup disiplinilmu bahasa, ilmu aqidah dan ilmu fiqih. Berdasarkan konstruksinya teori qiyas, sebagai produk nalar Arab, dapat dipolakan menjadi tiga otoritas diantaranya: otoritas kata, otoritas ashl dan otoritas keserba-bolehan. Menurut al-Jabiri, imam Syafi’i-lah yang paling bertanggung jawab atas pelembagaan teori qiyas dalam peradaban Arab-Islam. Ketika membatasi sumber hukum secara hirakis: al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, sesungguhnya imam Syafi’i ingin membatasi wilayah nalar Arab dalam bingkai sumber hukum yang memang sudah dikenal sebelumnya. Maka tidak heran bila nalar Arab berkisar pada teks, yang pada akhirnya aktivitas produksi pengetahuan lebih banyak kepada prinsip al-ashl fi al-nash la fi al-waqi’ (ashl adalah teks bukan realitas). Dari sudut pandang epistemologis, bangunan nalar Arab berkisar pada dilalah al-khithab (petunjuk wacana) baik petunjuk teks maupun kandungan teks. Petunjuk teks bermuara pada pembahasan antara lafadz dan makna, sementara petunjuk kandungan teks bermuara pada pembahasan teori qiyas. Dengan kata lain, penyelesaian masalah baru (al-far’) dirujukkan pada al-ashl dengan berpegang pada kandungan teks dan tetep berpijak pada hubungan lafadz dan makna, karena hanya dengan ini dapat diperoleh kandungan teks.[26]
Hubungan antara lafadz dan makan inilah yang menjadikan problematika utama teori qiyas, di mana teori qiyas sering terperangkap dalam penjelasan kebahasaan daripada intelektual-logis dan lebih memposisikan pada wilayah wacana daripada sistem nalar. Padahal hubungan antara lafadz-makna, ashl-far’, dalil-madlūl bukan sebuah keharusan karena hanya sekadar hubungan spekulatif. Menurut al-Jabiri, persoalan rekonstruksi nalar Arab adalah bagaimana merekonstruksi hubungan antar epistemologi. Hubungan tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis bukan sekadar untuk kepentingan ideologis karena hal semacam ini hanya akan menyudutkan epistemologi Burhani. Hubungan antar epistemologi ini seharusnya dibangun dengan baik dalam tataran manhaj, bahasa dan logika, maupun tataran pandangan dunia, teologi dan filsafat.
Pada rekontruksi antar hubungan epistemologi, al-Jabiri melucuti epistemologi Irfani yang dianggap musuh dalam selimut epistemologi Bayani. Menurutnya, Ibn Sina dan al-Ghazali-lah yang bertanggung jawab memasukkan sistem berpikir Irfani ini kedalam ranah pemikiran Islam yang sekaligus menjadikan akal Arab-Islam itu mandek. Dengan begitu, al-Jabiri ingin membangun prinsip-prinsip epistemologi Bayani diatas pondasi epistemologi Burhani. Karena Burhani merupakan sistem pengetahuan yang berdasarkan pada metode Burhan dalam rangka merumuskan kebenaran, caranya dengan mengaitkan antara akibat dan sebab (hukum kausalitas). Untuk mencari hukum kausalitas yang terjadi pada peristiwa-peristiwa alam, sosial, kemanusiaan dan keagamaan, nalar tidak memerlukan nash keagamaan karena sumber pengetahuan epistemologi Burhani adalah realitas.[27]
Relevansinya Bagi Ilmu-Ilmu Keagamaan
Setelah mengenal ketika corak epistemologi pemikiran keislaman di atas, langkah penting lain yang tidak kalah penting nilai fundamentalnya adalah menentukan hubungan diantara ketiganya. Bagaimana bentuk relasinya yang ideal di antara ketiganya? Jika hubungan antara ketiga corak epistemologi tersebut dipilih secara paralel maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dan persentuhan antara satu dengan lainnya dalam diri seorang ilmuwan dan ini akan berimplikasi pada perolehan nilai manfaat teoritis maupun praktis secara minimalis sekali. Sedangkan hubungan secara linier pada ujung-ujungnya akan menghadapi jalan buntu keilmuan karena dari ketiga epistemologi itu salah satunya akan menjadi primadona. Di lingkungan umat Islam yang pluralistik ini, pola hubungan yang baik antara ketiganya adalah sirkulasi dalam arti bahwa masing-masing corak epistemologi keilmuan agama Islam yang digunakan dalam studi keislaman dapat memahami kelemahan, keterbatasan dan kekurangan yang melekat pada diri masing-masing, yang kemudian bersedia mengambil manfaat dari temuan-temuan yang ditawarkan oleh tradisi keilmuan lain serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekurangan yang melekat pada diri sendiri.
Cara berpikir sempit dan spirit keilmuan demikian yang dimaksud dengan al-ta’wil al-‘ilmi dengan model kerja memanfaatkan gerak putar hermeneutis antara ketiga corak tradisi epistemologi keilmuan Islam yang telah baku. Dengan begitu, kekakuan, kekeliaruan, ketidak-tepatan dan kesalahan yang melekat pada masing-masing epistemologi pemikiran keagamaan Islam dapat dikurangi dan diperbaiki, setelah memperoleh masukan dan kritik dari jenis epistemologi yang datang dari luar dirinya baik dari Bayani, Irfani maupun Burhani. Maka, dalam pola relasi sirkulasi ini tidak menunjukkan adanya finalitas, ekslusivitas dan hegemoni keilmuan yang ada hanya tradisi dialog.[28]
Penutup
Inti kajian al-Jabiri sebenarnya tidak banyak berbeda dengan banyak pemikir liberal lain, seperti Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Adonis, Fatima Mernisi, dan lain-lain. Ia menolak metode Bayani yang dikembangkan oleh para fuqaha’ dan ulama ushūl al-fiqh karena dianggap lebih mengedepankan teks dari pada substansi teks. Al-Jabiri pun menyerang imam Syafi’i, kerena dianggap orang bertanggung jawab meletakkan dasar berpikir tersebut melalui karya monumentalnya, al-Risâlah.
Al-nidham al-ma’rifi al-bayani dikembangkan oleh para fuqaha’. Sistem berpikir ini sangat bergantung pada teks, teks yang berada diatas akal (filsafat). Ilmu fiqh, Tafsir, Filologi, merupakan produk episteme ini yang disebutnya sebgai al-ma’qul al-dini (rasionalitas keagamaan). Karakteristik utama episteme ini adalah ketergantungannya pada teks, bukan pada akal. Yang dimaksudkannya dengan teks disini adalah al-Qur’an dan Sunnah. Episteme ini menurut al-Jabiri sangat kuat sekali mendominasi pemikiran Arab Islam sehingga sejak dari awal kelahirannya sampai sekarang ia tidak menglami perkembangan.
Al-Jabiri juga mengkritisi metode Irfani yang dia asosiasikan dengan Syi’ah dan kaum Sufi. Disini, ia mengkritisi habis-habisan Ibn Sina dan al-Ghazali, dua tokoh yang selama ini dianggap antagonis. Menurutnya kedua pemikir inilah yang bertanggung jawab memasukkan sistem berpikir Irfani ini kedalam ranah pemikiran Islam yang sekaligus menjadikan akal Arab-Islam itu mandek.
Adapun episteme Burhani adalah episteme yang dibangun oleh filsafat Arab yang berekembang di Afrika Utara dan Spanyol. Ibn Rushd dianggap sebagai sosok yang paling sempurna merepresentasikan tipe Burhani ini. Tipologi sistem ini tidak berpegang pada nash semata, juga tidak pada intuisi, tapi pada akalnya Ibn Rushd dan eksperimen-nya Ibn Khaldun. Sesungguhnya, katanya lagi, inilah yang membuat Barat maju seperti sekarang ini. Para saintis Barat dengan jitu mengaplikasikan semangat rasionalisme Ibn Rushd dan empirisismenya dalam sistem peradaban mereka. Oleh sebab itu, lanjutnya, kalau kita ingin maju bersaing dengan realitas yang ada kita harus dapat mengembangkan semangat rasioanlisme dan juga empirisisme.
Dengan mengagungkan Ibn Rusyd, sebenarnya Jabiri ingin mengatakan bahwa kemajuan itu hanya bisa ditempuh dengan rasionalisme. Baginya, akallah yang bisa mengantar peradaban manusia ke puncak kegemilangannya. Sayangnya,”akal” yang disebut al-Jabiri itu adalah akal yang dikonsepsikan oleh Barat, yaitu akal positivis yang hanya berpaut pada data-data eksperimental. Disamping itu al-Jabiri sepertinya sengaja melupakan bahwa rasionalisme abad Pencerahan itu sendiri saat ini sedang mendapat kritikan tajam, bukan hanya dari kalangan ilmuwan Muslim tapi juga dari kalangan intelektual Barat sendiri.
Al-Jabiri juga lupa, bahwa revolusi sains (scientific revolution) terjadi di Barat karena orang-orang seperti Bacon, Descartes, dan Newton melakukan kritik terhadap teori-teori fisika Aristotle. Artinya Barat maju bukan karena mereka mengadopsi padangan-pandangan Ibn Rushd yang Aristotelian, tapi sebaliknya, sains mereka berkembang justru karena mereka meninggalkan teori-teori fisika Aristotle.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Jabiri, Muhammad Abid . Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi: dirasâh taḫliliyyah naqdiyyah li nadzm al-ma’rifah fi al-șaqâfah al-‘arâbiyyah. Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-Murabiyyah, 1986.
Al-Jabiri, Muhammad Abid. Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
Amien, Miska Muhammad . Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam. Jakarta: UI Press. 1983.
Dkk, Syamsul Arifin . Spritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan. Yogyakarta: SIPRESS, 1996.
Hamerma, Harry. Pintu Masuk ke Dunia Filsafat. Yogyakarta: Karisusu, 1992
Kholish, Nurul.Nalar Irfani dalam Kancah Problema di Indonesia. Yogyakarta: 2009.
Mustari. Memahami Pemetaan Epistemologi Islam Muhammad ‘Abid al-Jabiri. Jurnal Thaqafiyyat Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2010.
Nirwan Syafrin. Kritik Terhadap Kritik Akal Islam Al-Jabiri. Jurnal Islamiya, Thn I No. 2 Juni-Agustus 2004.
Ridho, Muhammad Rasyid. Epistemologi Islamic Studies Kontemporer: Relasi Sirkular Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani. Surabaya: Jurnal KRASA, Vol. X No. 2 Oktober, 2006.
Soleh, A. Khudori. Epistemologi Bayani, http://www.id.shvoong.com/tags/episemologi-Bayani, 05 Desember 2012.
The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu. Bandung: The Science and Technology Stues Foundation, 1987.
Zulkarnain. Pemikiran Kontemporer Muhammad Abid Al-Jabiri Tentang Turats Dan Hubungan Arab Dan Barat. artikel diakses tanggal 5 Desember 2012 dari http://www.litagama.org/Jurnal/Edisi6/aljabiri.htm.
[1] Harry Hamerma, Pintu Masuk ke Dunia Filsafat (Yogyakarta: Karisusu, 1992), hlm. 15. Lihat juga Miska Muhammad Amien, Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 1.
[2] The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu (Bandung: The Science and Technology Stues Foundation, 1987), hlm. 83.
[3] Dikutip Miska Muhammad Amien, Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam (Jakarta: UI Press, 1983), hlm.11.
[4] Ibid.
[5] Muhammad Abid Al Jabiri, Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 19.
[6]konsep yang diusung oleh Karl Marx yang dipengaruhi oleh filosof abad pertengahan.
[7] Zulkarnain, Pemikiran Kontemporer Muhammad Abid Al-Jabiri Tentang Turats Dan Hubungan Arab Dan Barat, artikel diakses tanggal 5 Desember 2012 dari http://www.litagama.org/Jurnal/Edisi6/aljabiri.htm
[8] Nirwan Syafrin, “Kritik Terhadap Kritik Akal Islam Al-Jabiri,” Islamiya, Thn I No. 2 (Juni-Agustus 2004) hlm. 44.
[9] Ibid ., hlm. 45.
[10] Zulkarnain, “Pemikiran Kontemporer Muhammad Abid Al-Jabiri Tentang…..
[11] Ibid.
[12] Mustari, Memahami Pemetaan Epistemologi Islam Muhammad ‘Abid al-Jabiri (Yogyakarta: Thaqafiyyat Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2010), hlm. 251.
[13] Muhammad Abid Al Jabiri, Formasi Nalar Arab………, hlm. 169.
[14] Muhammad Rasyid Ridho, Epistemologi Islamic Studies Kontemporer: Relasi Sirkular Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani (Surabaya: Jurnal KRASA, Vol. X No. 2 Oktober, 2006), hlm. 886.
[15] Ibid., hlm. 887.
[16] A. Khudori Soleh, Epistemologi Bayani, http://www.id.shvoong.com/tags/episemologi-Bayani, 05 Desember 2012.
[17] Ibid.
[18] Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi: dirasâh taḫliliyyah naqdiyyah li nadzm al-ma’rifah fi al-șaqâfah al-‘arâbiyyah (Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-Murabiyyah, 1986), hlm. 113.
[19] Mustari, Memahami Pemetaan Epistemologi Islam ……., hlm. 254.
[20] Nurul kholish , Nalar Irfani dalam Kancah Problema di Indonesia ( Yogyakarta: 2009), hlm. 6.
[21] Muhammad Rasyid Ridho, Epistemologi Islamic Studies Kontemporer..…., hlm. 887.
[22] Mustari, Memahami Pemetaan Epistemologi Islam ……., hlm. 255.
[23] Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi….., hlm. 383.
[24] Ibid., hlm.392-393.
[25] Syamsul Arifin dkk, Spritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan (Yogyakarta: SIPRESS, 1996), hlm. 108.
[26] Mustari, Memahami Pemetaan Epistemologi Islam ……., hlm. 259.
[27] Ibid., hlm. 260.
[28] Muhammad Rasyid Ridho, Epistemologi Islamic Studies Kontemporer…, hlm. 890-891.